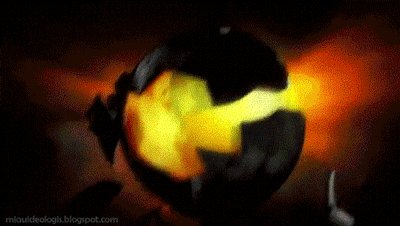Sudah menjadi rahasia umum dan hampir semua orang tahu apa kaitan antara partai politik, kekuasaan dan uang. Dalam praktek sistem demokrasi ketiganya memiliki kaitan yang sangat erat, teramat erat dan kuat. Partai politik sebagai kendaraan untuk mencapai kekuasaan tidak mungkin bisa berjalan tanpa uang. Uang menjadi alat politisi untuk mencari kekuasaan dan jabatan. Selanjutnya kekuasaan dan jabatan mereka gunakan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Begitu seterusnya, inilah bisnis kekuasaan. Betapa tidak, di saat partai politik tidak lagi memerankan fungsinya dengan benar terutama dalam hal melakukan pendidikan politik di tengah-tengah masyarakat, partai politik cenderung melakukan cara-cara instan untuk mendapatkan suara dan dukungan. Di sinilah logika uang selalu dimainkan. Yang banyak duit dialah yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemenang. Hal ini terjadi baik dalam perebutan kursi di internal partai atau di saat pemilu atau pemilukada. Untuk ongkos pemilukada di DKI Jakarta saja misalnya, menurut Sekjen Transparency International Indonesia Teten Masduki, calon gubernur yang memakai parpol sebagai kendaraan harus memberikan mahar yang nilainya mencapai Rp 600 miliar. Itu belum termasuk dana pendongkrak popularitas, yang menurut studi Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis, minimal Rp 100 miliar. (Media Indonesia, 13/02/2012). Kalau ongkos menjadi kepala daerah sudah sedemikan besar, lalu bagaimana dengan ongkos menjadi presiden ?. Tentunya jika hanya miliyaran rupiah yang dikantongi, pasti tidak cukup.
Dari mana uang itu ?
Mengacu pada undang-undang No 2/2011 tentang partai politik, khusus pasal 34-35 yang mengatur keuangan partai politik. Disebutkan bahwa sumber legal keuangan partai politik secara umum ada tiga: iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum; dan bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (uu no 2/2011 pasal 34 ayat 1-3).
Sumbangan yang sah menurut hukum, sebagaimana disebutkan dalam pasal 35, adalah (1) sumbangan dari perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART, (2) sumbangan dari perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai 1 milyar perorang dalam jangka satu tahun, (3) sumbangan dari perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai 7,5 milyar pertahun.
Sementara dana dari APBN/APBD hanya diberikan kepada partai yang meraih kursi di DPR/DPRD. Untuk tingkat pusat subsidi pemerintah dipatok sebesar Rp 108 (seratus delapan rupiah) persuara. Secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan Rizal Djalil (Anggota VI Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), sebanyak 9 parpol di DPR mendapat total dana Rp 9,1 miliar per tahun dari dana APBN (detiknews.com, 28/11/2011). Partai demokrat, sebagai partai pemenang pemilu mendapatkan subsidi sebesar 2,3 milyar dari sekitar 21 juta suara yang diperolehnya, menyusul partai-partai lain.
Lalu bagaimana dengan iuran anggota? Dalam undang-undang, seolah ia merupakan pendapatan utama partai dengan ditempatkan di nomor pertama. Tapi, pada kenyataannya ditetapkan sumber ini tak ubahnya sebagai hiasan, pemanis undang-undang belaka. Studi yang dilakukan Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Yayasan Manikaya Kauci (YMK), Komite Pemantau Legislatif (Kopel), dan Kemitraan untuk Integritas dan Pembaruan Tata-Pemerintahan, mendapati tidak satu pun partai yang menggalang sumber ini. (Koran Republika, 13/01/2012). Artinya, tidak ada partai yang berhasil mengumpulkan uang recehan dari konstituen atau pun simpatisannya. Yang ada malah sebaliknya, partai harus menggelontorkan dana yang besar untuk mereka atau membayar suara mereka. Ini wajar, selain secara teknis penarikan iuran itu sulit dilakukan, juga jumlahnya tidak signifikan dibanding kebutuhan partai, apalagi jika hal itu dipandang malah memberatkan anggota.
Singkat kata, uang legal sebagaimana “dihalalkan” undang-undang tidak mungkin mencukupi seluruh biaya partai. Partai butuh “pemasok” lain selain sumber “halal” tersebut. Di sinilah, korupsi dalam praktek demokrasi menjadi keniscayaan dan bahkan sudah menjadi bagian dari praktek tersebut. Tak heran, dalam kondisi seperti ini masyarakat menjadi mudah percaya terhadap berbagai kasus yang membelit para pejabat yang jumlahnya milyaran hingga triliyunan rupiah itu. Ada kasus century 6,7 T, proyek Ambalang bernilai 1,2 T, proyek alat bantu olah raga 75 M, pembangunan Wisma Atlet di Palembang 200 M, pembangunan sarana prasarana atlet di Jawa Barat 180 M, dll.
Usaha untuk mengurangi beban partai dalam pemilu, yaitu dengan menyerahkan pembiayaan pemilu kepada masing-masing caleg atau calon kepala daerah ternyata juga tidak serta merta menekan korupsi. Yang ada justru sebaliknya, semakin hari korupsi semakin merajalela. Pelakunya bukan hanya elit partai ataupun pejabat pusat, tetapi juga para pejabat dan kepala daerah. Laporan mendagri Gamawan Fauzi tahun lalu menyebutkan bahwa dari 155 kepala daerah yang jadi tersangka korupsi, 74 orang di antaranya gubernur. Sementara menurut Indonesia Coruption Watch, sepanjang 2011 mencatat 99 anggota DPRD dan DPR menjadi tersangka korupsi.
Bisa dihentikan ?
Masyarakat tentu tidak berhenti berharap bahwa kasus demi kasus korupsi bias dituntaskan dan memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi yang lain. Namun, kenyataan berbicara lain, penegakan hukum di Indonesia, kian hari kian buruk. Hal ini nampak seperti pada lemahnya penegakan hukum terkait kasus dana talangan Bank Century, skandal Nazarudin, dan kasus Nunun Nurbaeti, yang saat ini menjadi soratan utama masyarakat. KPK sebagai lembaga superbody seharusnya bisa bergerak cepat. Namun sepetinya para koruptor itu bisa bergerak lebih cepat lagi, lebih rapi, dan lebih pandai. Sehingga, korupsi yang baunya begitu menyengat ini, sulit sekali dibuktikan. Hingga KPK jilid 3, bangsa ini belum bisa bernafas lega dari ancaman korupsi. Justru yang ada koruptor semakin terlatih, walaupun gerak mereka semakin dibatasi. Hal ini tiada lain, karena korupsi sudah menjadi kebutuhan. Ibarat orang mencari makan, ia akan berusaha sekuat tenaga agar ia tetap bisa makan, walaupun ia harus mencuri. Begitu pun para pejabat, selama mereka hidup dalam sistem demokrasi, selama itu pula ia harus mendulang harta untuk mendapatkan kembali kekuasaan itu, atau paling tidak bagaimana dia bisa bertahan pada kekuasaan itu.
Kesulitan dalam menghentikan hubungan buruk antara partai politik, kekuasaan dan uang dalam praktek demokrasi wajar terjadi. Betapa tidak, kekuasaan dalam sistem demokrasi sudah menjadi barang mewah. Jabatan adalah identik dengan prestise, martabat, kehormatan, bahkan ladang penghasilan yang subur. Satu-satunya jalan untuk menghentikannya tiada lain dengan mengembalikannya kepada cara pandang Islam terhadap kekuasaan. Dalam Islam kekuasaan adalah amanah. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar, Rasulullah Saw. bersabda:
إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها (رواه مسلم)
“Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanat dan pada hari akhirat kepemimpinan itu adalah rasa malu dan penyesalan, kecuali orang yang mengambilnya dengan haq serta melaksanakan tugas kewajibannya.” (HR. Muslim).
Mengembalikan kekuasaan kepada konsep Islam, bukan hanya berarti bahwa kekuasaan harus diserahkan kepada kaum muslimin. Namun, juga berarti menerapkan seluruh konsep Islam dalam hal kekuasaan, melalui tegaknya syariah dalam bingkai khilafah Islam. Berharap akan lahirnya para pejabat yang amanah dari sistem demokrasi adalah angan-angan belaka. Parpol atau orang boleh saja berganti, namun selama sistemnya tidak dirubah, maka parpol dan pejabat berwatak sama pun akan kembali lahir dan bahkan lebih piawai. (Ade Sudiana)[hizbut-tahrir.or.id]
The KHILAFAH Channel
khilafah on livestream.com. Broadcast Live Free